- Oleh: M. Azis Tunny, Ketua Lembaga Studi Politik dan Demokrasi (LSPD)
Jakarta,- Di era media sosial yang gaduh dan tak bertepi, satu kata bisa menimbulkan badai. Kritik bisa berubah jadi hujatan, perbedaan pendapat bisa menjelma jadi serangan pribadi. Di tengah derasnya arus opini dan cibiran yang datang dari segala arah, Bahlil Lahadalia memilih jalan tenang untuk menyikapinya, yakni memaafkan.
Bagi sebagian orang, sikap itu tampak sederhana. Tapi bagi seseorang yang meniti karier secepat dan sekeras Bahlil, keputusan untuk memaafkan bukan perkara mudah. Ia bukan sosok yang lahir dari elite politik atau bisnis. Ia anak kampung dari Kepulauan Banda (Maluku) dan besar di Fakfak (Papua Barat), yang masa mudanya diisi dengan berjualan kue keliling dan bekerja serabutan demi menyambung hidup.
Hidup yang keras membentuknya menjadi sosok yang tangguh, tetapi juga tahu arti empati. Ia mengaku sudah sering dihina, sejak masih kecil. Sehingga, ketika gelombang hinaan datang di puncak karirnya, ia tidak terpancing untuk membalas. Ia sudah lama belajar bahwa kemarahan hanya akan menenggelamkan akal sehat.
Namun, di balik ketenangannya, ada badai besar yang sedang dihadapinya. Bahlil memang melesat cepat, dari pengusaha muda, Ketua Umum HIPMI, hingga dipercaya Presiden menjadi Menteri Investasi, lalu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Laju karier yang cepat itu membuat sebagian kalangan merasa “tak nyaman.”
Di mata beberapa pengusaha senior, Bahlil dianggap terlalu muda untuk memegang kendali kebijakan strategis. Sementara di lingkaran kekuasaan, ada pula yang melihatnya sebagai “orang luar” yang tak mudah dikendalikan.
Di ranah kebijakan, keberanian Bahlil untuk mengambil langkah-langkah besar membuat banyak pihak merasa terancam. Sebagai Menteri Investasi dan kemudian Menteri ESDM, ia mengambil keputusan yang tegas, bahkan berisiko tinggi secara politik. Ia mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah, menutup pintu bagi perusahaan-perusahaan yang tak menjalankan kewajiban lingkungan dan kewajiban fiskal. Langkah ini langsung mengguncang “peta kuasa” para pemain lama di sektor tambang.
Tak berhenti di situ, ia memperketat kran impor migas, menutup ruang bagi para pemburu rente yang selama ini menikmati margin besar dari kebijakan impor yang longgar. Keputusan itu jelas tidak populer di kalangan tertentu, terutama mereka yang selama bertahun-tahun menggantungkan keuntungan pada sistem yang tidak efisien dan penuh celah.
Akibatnya, Bahlil tak hanya berhadapan dengan kritik publik, tapi juga dengan jaringan kepentingan besar yang tak segan menggunakan berbagai cara untuk menjatuhkannya.
Namun, di tengah tekanan yang begitu besar, Bahlil tidak berubah. Ia tetap tampil tenang, tidak reaktif, dan terus bekerja. Ia tidak membalas serangan dengan serangan. Ia percaya, waktu dan hasil kerja akan menjadi pembela terbaik.
“Kalau ada yang menghina, saya maafkan. Saya kan sudah biasa dihina sejak masih kecil,” kata Bahlil. Sebuah kalimat pendek, tapi di baliknya tersimpan kedewasaan yang langka di dunia politik kita.
Bahlil tahu bahwa memaafkan bukan berarti menyerah. Memaafkan, bagi dirinya, adalah cara menjaga fokus. Ia tidak ingin energi yang seharusnya digunakan untuk membangun negeri habis hanya untuk meladeni serangan dan fitnah.
Ia lebih memilih membiarkan kinerja dan kebijakan yang berbicara. Dalam setiap langkahnya, ada kesadaran bahwa membenahi sistem berarti siap kehilangan popularitas, bahkan siap dijadikan musuh oleh mereka yang selama ini menikmati “kenyamanan lama.”
Sikap ini mengingatkan kita bahwa kebesaran sejati bukan terletak pada seberapa tinggi seseorang berdiri, tetapi seberapa tenang ia tetap berdiri ketika badai datang. Dunia politik dan bisnis adalah arena yang keras, penuh kepentingan dan intrik.
Tapi di tengah itu semua, Bahlil menunjukkan sisi manusiawi seorang pemimpin. Berani mengambil keputusan yang tidak populer, dan tetap rendah hati ketika diserang.
“Hanya saya tidak mau ada pihak-pihak yang mencoba untuk mendorong keinginannya mengintervensi kebijakan negara. Karena bagi saya, menteri itu pejabat negara, pembantu presiden. Kalau apa yang sudah diarahkan oleh presiden untuk menjaga marwah negara, menjalankan kedaulatan, dengan segala hormat, jangankan selangkah, sejengkal pun saya tidak akan mundur,” tegasnya dihadapan para wartawan.
Dalam diamnya, kita melihat kekuatan. Dalam maafnya, kita melihat kebijaksanaan. Dan dalam keberaniannya, kita belajar bahwa menjadi pemimpin berarti siap berjalan sendirian, selama langkah itu untuk kebaikan yang lebih besar.
Mungkin inilah makna sejati kebesaran jiwa yang sesungguhnya. Bahwa di tengah fitnah, tekanan, dan upaya menjatuhkan, masih ada ruang di hati untuk memaafkan. Karena seperti kata Bahlil, “Kita boleh berbeda, tapi jangan kehilangan rasa hormat.” Sebuah pesan sederhana, tapi justru itulah yang paling sulit dilakukan di zaman yang penuh kemarahan ini.*** (AT)

















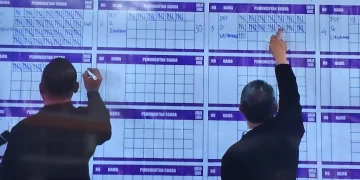















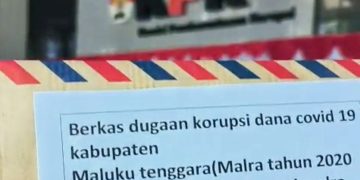




























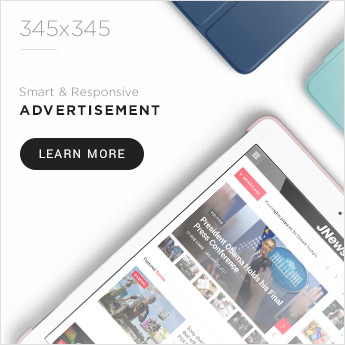















Discussion about this post