Jakarta,— Setiap kali Sumpah Pemuda tiba, hati saya selalu bergetar. Bukan hanya karena maknanya yang besar, tapi karena di tengah gegap gempita peringatan itu, suara dari timur Indonesia sering kali terdengar paling pelan atau bahkan nyaris tak terdengar sama sekali. Maka, ketika dari arena Musyawarah Nasional ke-V Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) di Kemayoran terdengar seruan lantang “Indonesia juga punya kami,” saya tahu: inilah panggilan hati kami, anak-anak dari tanah yang jauh tapi tetap Indonesia seutuhnya.
Seruan itu bukan sekadar kalimat. Ia lahir dari kegelisahan panjang, dari pengalaman menjadi saksi bagaimana rasisme, dikotomi sosial, dan ketimpangan masih saja bersembunyi di balik kata “persatuan”.
Dunia mungkin telah lama memperalat rasisme untuk menindas, tapi kini bayangannya juga tumbuh di antara kita sendiri. Pengelompokan berdasarkan suku dan asal wilayah menciptakan jarak yang halus tapi nyata, jarak yang membuat sebagian dari kami harus bekerja dua kali lebih keras untuk dianggap sama.
Realitas ini terasa jelas di ruang sosial dan politik negeri ini. Dominasi wilayah tertentu seolah menjadi pola tetap. Jawa dan Sumatra masih sering disebut sebagai “pusat,” sementara wilayah timur seperti Maluku, Papua, atau Nusa Tenggara terus berjuang untuk mendapat ruang yang setara. Dan setiap kali ada anak timur yang melangkah ke panggung nasional, prasangka seolah menunggu di pintu.
Saya melihat bagaimana sosok seperti Bahlil Lahadalia menembus batas-batas itu. Lahir sederhana, menempuh jalan panjang penuh keringat dan kerja keras, Bahlil kini berdiri sebagai simbol anak bangsa yang tak menyerah pada keterbatasan.
Ia vokal memperjuangkan pemerataan ekonomi, mendorong hilirisasi tambang, mengupayakan kepemilikan saham Freeport untuk Indonesia, bahkan membuka akses rakyat agar bisa mengelola sumber daya alamnya sendiri. Dari energi baru terbarukan sampai diplomasi investasi lintas negara, kerja kerasnya nyata.
Namun, bahkan di tengah semua itu, cibiran dan serangan bernada rasis masih datang. Dunia digital yang seharusnya jadi ruang gagasan justru sering berubah menjadi arena kebencian.
Kadang saya berpikir: kenapa masih ada yang sulit menerima bahwa keberhasilan anak timur juga keberhasilan Indonesia? Bahwa nasionalisme bukan milik satu suku atau satu pulau saja?
Dari refleksi itulah, saya semakin yakin: kita perlu kembali ke ruh Sumpah Pemuda. Kembali pada janji bahwa kita bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Bahwa rasisme, iri hati, dan keserakahan tak boleh lagi menjadi alat untuk membeda-bedakan.
Hari ini, di tengah dinamika pemerintahan yang penuh tantangan, kita melihat bagaimana Presiden Prabowo Subianto berupaya menenangkan arah bangsa, memimpin dengan kharisma dan diplomasi yang menumbuhkan harapan. Di sisi lain, ada tokoh-tokoh muda seperti Bahlil yang terus bergerak, membangun energi nasional, investasi, dan kemandirian bangsa. Inilah bukti bahwa kebangkitan Indonesia bukan lagi monopoli satu wilayah.
Kami, dari timur, juga bagian dari cerita besar itu. Kami bukan figuran, bukan pelengkap. Kami adalah anak bangsa yang berdiri sejajar, membawa semangat kerja keras dan cinta tanah air yang sama.
Dalam semangat Sumpah Pemuda tahun ini, saya ingin mengingatkan: berhentilah memandang kami dengan kacamata perbedaan. Dengarkan kami, lihat kerja kami, rasakan semangat kami. Karena Indonesia juga punya kami, anak-anak dari timur, yang siap berdiri, berjuang, dan mengabdi untuk negeri yang kita cintai bersama.***

































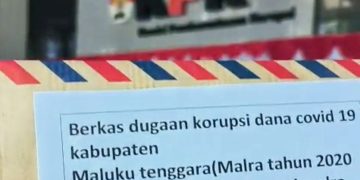




























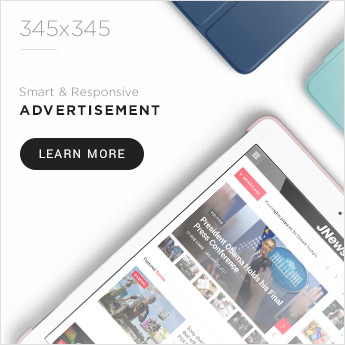















Discussion about this post