Jakarta, Maluku– Konflik kekerasan yang melibatkan warga Kailolo, Kei dan Seram Timur, di kawasan STAIN Ambon beberapa waktu lalu, telah menyisakan kegelisahan sosial yang tidak biasa. Peristiwa konflik yang kerap terjadi itu bukan hanya soal bentrokan fisik, melainkan juga penanda rapuhnya relasi antarkomunitas.
Ketika konflik berpotensi meluas dan memantik sentimen yang lebih besar, Ketua Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM), Umar Kei Ohoitenan, mengambil inisiatif untuk mediasi pertemuan damai antara warga yang berkonflik. Dari Jakarta, dia mengajak Ketua Ormas AKUMALUKU, Ali Fanser Marasabessy, untuk sama-sama turun ke Maluku merajut kohesi sosial yang sempat terkoyak.
Inisiatif untuk turun langsung menyelesaikan konflik tersebut didasari atas keprihatinan dan dorongan tanggung jawab moral agar kekerasan tidak berkembang menjadi luka sosial yang lebih dalam dan berkepanjangan.
Dari Jakarta, keduanya memulai ikhtiar damai. Berniat ingin mendamaikan konflik orang basudara di Ambon, Umar Kei dan Ali Fanser lantas mempertemukan para raja, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemuda dari ketiga wilayah. Pertemuan yang berlangsung di Ballroom Hotel Santika Premiere Ambon pada Jumat Sore (16/01/2026) itu diakhiri dengan ikrar janji damai yang ditandatangani bersama. Mereka yang hadir saling berjabat tangan, dan saling rangkul satu sama lain.
Pertemuan awal ini berlangsung damai, dan menjadi fondasi penting sebelum proses kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di Kailolo dan Kei. Pilihan untuk hadir di ruang-ruang sosial tempat konflik berakar menunjukkan kesadaran bahwa perdamaian tidak cukup dibangun melalui pernyataan simbolik, tetapi menuntut kehadiran dan keterlibatan yang nyata.
Umar Kei dan Ali Fanser dikenal sebagai tokoh pemuda yang tumbuh dari basis grassroot (akar rumput). Keduanya lama berinteraksi dengan dinamika sosial masyarakat bawah, memahami bahasa emosi publik, sekaligus mengetahui batas tipis antara solidaritas dan konflik. Pengalaman itu membentuk karakter kepemimpinan yang keras, lugas, dan apa adanya. Mereka tidak memilih jalan kompromi yang absurd, karena konflik sosial membutuhkan kejelasan sikap, bukan bahasa yang sifatnya hanya menenangkan sesaat.
Umar Kei berasal dari Tamngil Nuhuten dan Danar di Kepulauan Kei (Maluku Tenggara). Ia kerap tampil dengan karakter kepemimpinan yang tegas dan lugas, dikenal sebagai sosok yang tidak gemar berputar-putar dalam bahasa, tetapi langsung pada pokok persoalan.
Ketegasan Umar Kei bukan tanpa alasan. Dirinya memahami psikologi kolektif warga Maluku, bahwa harga diri, identitas dan sejarah, selalu menjadi bahan bakar yang mudah menyulut amarah. Karena itu, pendekatannya tidak menggurui. Ia lebih memilih mengingatkan, bahwa orang Kailolo, Seram Timur dan Kei sama-sama lahir dari kebudayaan yang menjunjung tinggi pela-gandong, dan persaudaraan lintas pulau. Ini menunjukkan, ketegasannya berpadu dengan kesadaran historis.
Sementara Ali Fanser berasal dari desa Kailolo di Kepulauan Lease (Maluku Tengah), berdiri pada garis yang sama. Ia juga keras dalam prinsip dan gamblang dalam berbicara. Ketegasannya selalu disertai penekanan pada pentingnya menjaga relasi antarkomunitas yang telah lama terbangun. Konflik, dalam pandangannya, bukan pertarungan identitas, melainkan kegagalan sementara dalam merawat hubungan sosial yang seharusnya dijaga bersama.
Dimensi lebih dalam pada ikhtiar keduanya kenapa harus turun langsung menyelesaikan konflik adalah hubungan kekerabatan personal. Umar Kei dan Ali Fanser meyakini mereka memiliki ikatan darah yang bersumber dari satu pancaran leluhur yang sama. Keduanya terhubung bukan hanya oleh kepedulian sosial, tetapi juga oleh ikatan kekerabatan yang dipercaya bersumber dari satu moyang yang sama, yang dalam tradisi lisan dikenal sebagai nenek Boiratan.
Ikatan ini membuat konflik tersebut tidak dipandang sebagai persoalan orang lain, melainkan urusan keluarga besar yang harus diselesaikan tanpa mewariskan luka berkepanjangan. Pendekatan ini menjadikan pesan damai yang mereka sampaikan karena memiliki bobot moral yang lebih kuat.
Sebagai tokoh pemuda, Umar Kei dan Ali Fanser juga memiliki relasi yang cukup baik dengan elit politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Relasi ini tidak digunakan untuk membangun panggung kekuasaan, melainkan dimanfaatkan secara fungsional, membuka jalur komunikasi, menurunkan tensi, dan memastikan bahwa upaya damai mendapat ruang serta dukungan yang memadai. Posisi mereka yang berada di antara akar rumput dan elite memberi kelebihan tersendiri dalam menjembatani kepentingan sosial dan stabilitas yang lebih luas.
Pertemuan-pertemuan damai yang difasilitasi melibatkan figur-figur kunci di tingkat komunitas. Dengan cara itu, kesepakatan yang lahir tidak berhenti sebagai pernyataan elite, tetapi memiliki peluang untuk dijaga bersama. Proses ini sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian konflik horizontal tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada pendekatan keamanan. Ia membutuhkan keterlibatan sosial, keteladanan, dan keberanian untuk mengakui kesalahan.
Langkah Umar Kei dan Ali Fanser berlangsung tanpa sorotan berlebihan. Tidak ada klaim kepahlawanan, tidak ada upaya menempatkan diri sebagai pusat perhatian. Tulisan ini pun tidak bermaksud mengglorifikasi keduanya, tapi sebatas apresiasi atas upaya mereka mendamaikan warga yang berkonflik. Dalam situasi ketika emosi publik mudah dipicu oleh provokasi dan narasi identitas, ajakan untuk berdamai dan menahan diri justru menjadi nilai yang paling sulit, sekaligus paling dibutuhkan.
Konflik antara warga Kailolo, Seram Timur dan Kei, memberi pelajaran bahwa kekerasan horizontal selalu menyisakan kerugian yang sama. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Upaya menghentikannya menuntut lebih dari sekadar niat baik. Ia memerlukan keberanian untuk berkata cukup, kesediaan untuk duduk bersama, dan ketegasan untuk tidak mewariskan luka kepada generasi berikutnya.
Pada akhirnya, ajakan untuk menahan diri bukan sekadar pilihan moral individual. Ia adalah tanggung jawab sosial untuk merawat negeri dan masa depan bersama. Dalam konteks itulah, ikhtiar Umar Kei dan Ali Fanser layak dibaca sebagai pengingat bahwa perdamaian sering lahir dari kerja-kerja sunyi, dari tokoh-tokoh pemuda akar rumput yang memahami masyarakatnya, memiliki akses pada kekuasaan, namun memilih menggunakan keduanya untuk mencegah luka, bukan memperlebar jurang.***



























































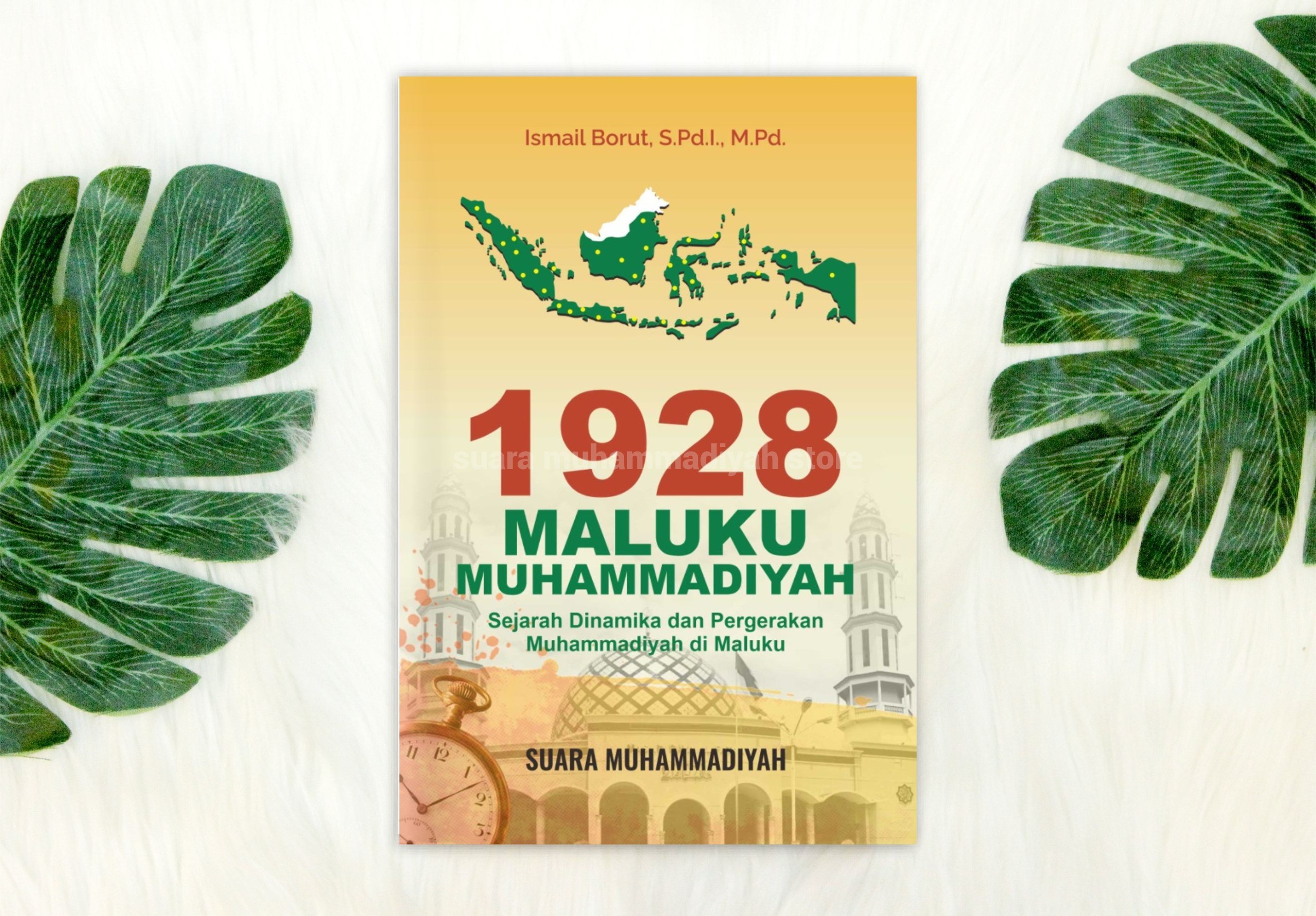

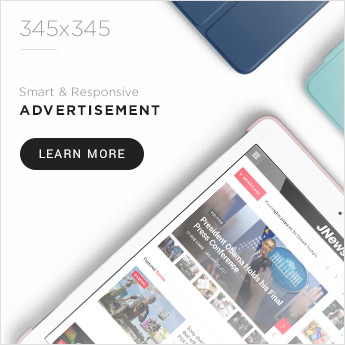















Discussion about this post