Jakarta,- Bicara soal politik Indonesia hari ini, kita seakan sedang menyeruput secangkir kopi pahit. Tidak semua orang bisa menikmatinya, apalagi ketika disuguhkan tanpa gula, dan tanpa kemewahan. Tapi bagi sebagian orang, justru di situlah kenikmatannya. Diseruput pelan-pelan, dinikmati rasa getirnya.
Salah satu figur yang tengah mencuri perhatian dalam lanskap ini adalah Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar. Dalam forum Diklat Kader Muda Nasional AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar) pada 3 Oktober 2025 lalu, ia membagikan kisah perjuangannya. Ia bercerita bagaimana dirinya sudah berkali-kali “dikepung elite,” dijegal, bahkan dipinggirkan. Namun alih-alih mengeluh, ia memilih untuk menikmati setiap tantangan itu.
Dengan santai namun penuh pesan mendalam, Bahlil menyatakan “Om suka itu. Om suka!” Sebuah pernyataan ringan, terdengar seperti jokes, tapi menyimpan filosofi hidup yang kuat tentang mentalitas bertahan dalam kerasnya politik Indonesia. Ia menyamakan perjuangannya dengan menyeruput kopi pahit yang tidak diteguk sekali habis. Tetapi dinikmati pelan-pelan, walau getir.
Apa yang ia ungkapkan bukan hanya pengalaman personal. Itu adalah potret sistemik dari wajah politik Indonesia hari ini. Dunia politik kita masih belum sepenuhnya memberi ruang untuk seseorang mencapai posisi puncak tanpa memiliki koneksi, tanpa trah, dan tanpa modal besar. Mereka yang bukan bagian dari lingkaran elite akan lebih sering berjalan sendiri, dengan jalur yang lebih terjal.
Bahlil datang dari luar lingkaran itu. Ia bukan anak jenderal, bukan anak konglomerat, bukan pewaris politik. Ia berasal dari Papua, dari daerah yang selama ini sering hanya menjadi penonton di panggung politik nasional. Ia menembus sistem bukan dengan pintu belakang, melainkan lewat perjuangan panjang. Ia pernah kalah, jatuh, terluka, namun tetap bertahan.
Yang menarik dari pidato Bahlil bukan hanya soal siapa dia, dan dari mana dia berasal, tetapi pada penekanannya terhadap pentingnya menikmati proses. Dalam politik yang kian serba instan, di mana popularitas sering mengalahkan substansi, dan pencitraan lebih utama ketimbang rekam jejak, pesan ini terasa menyegarkan. Kepemimpinan, kata Bahlil, dibentuk oleh proses jatuh-bangun. Bukan dari panggung yang dibangun semalam, tapi dari jalan panjang yang ditempuh dengan sabar.
Kita menyaksikan semakin banyak politisi muda yang lebih fokus pada sorotan kamera ketimbang perdebatan nilai. Mereka lebih sibuk menjadi viral daripada membangun gagasan. Dalam iklim seperti ini, ajakan untuk menghargai proses adalah bentuk perlawanan kultural. Sebuah pengingat bahwa daya tahan lebih penting daripada ketenaran instan yang sesaat.
Tak kalah penting, Bahlil juga menyentil persoalan mendasar lain dalam politik Indonesia yakni pewarisan kekuasaan. “Tidak ada lagi ini anak jenderal, anak konglomerat, anak menteri,” katanya. Ini bukan sekadar retorika. Ini kritik halus terhadap struktur kekuasaan yang cenderung eksklusif. Di beberapa partai politik, jenjang kepemimpinan masih cenderung diwariskan, bukan melalui pertarungan yang terbuka.
Dalam lanskap seperti ini, orang seperti Bahlil adalah anomali. Justru karena ia anomali, ceritanya menjadi penting. Ia membuktikan bahwa elite bukan benteng tak tergoyahkan. Bahwa mereka yang lahir dari pinggiran, tetap punya peluang untuk masuk ke pusat menantang status quo, membawa narasi baru, dan mengubah arah angin.
Tentu kita sadar, politik tetap mahal. Biaya kampanye, ongkos sosial, tekanan struktural, dan budaya patrimonial yang masih dominan adalah tembok tinggi yang sulit dilompati. Tapi kisah seperti Bahlil menunjukkan bahwa jalur itu, meski sempit, tetap masih mungkin untuk dilalui. Justru karena sulit, maka kisahnya menjadi inspiratif. Bukan karena sempurna, tapi karena nyata.
Kisah Bahlil semakin bermakna karena konteks asal-usulnya. Ia berasal dari Papua, dari pinggiran geografis dan struktural dalam peta kekuasaan nasional. Selama bertahun-tahun, tokoh-tokoh dari wilayah timur Indonesia nyaris tak pernah berada di jantung kekuasaan. Dalam diri Bahlil, banyak anak muda dari daerah melihat harapan, bahwa politik bukan lagi monopoli elite Jakarta.
Namun penting digarisbawahi, tulisan ini bukan glorifikasi terhadap satu sosok. Tokoh bisa naik, bisa juga jatuh. Tapi narasi perjuangannya menyimpan nilai penting untuk direnungkan. Politik kita tidak kekurangan figur, tapi sering kekurangan narasi yang menginspirasi. Narasi tentang keberanian melawan sistem, tentang kejujuran dalam menghadapi kenyataan, dan tentang kapasitas yang tumbuh dari keterbatasan.
Kita mungkin belum hidup dalam sistem meritokratis yang ideal. Tapi setiap kali ada yang berhasil menembus batas sosial-politik tanpa privilege, sesungguhnya kita sedang menyaksikan tanda-tanda perubahan. Politik tidak harus selalu digerakkan oleh pewaris yang punya privilage, ia juga bisa dibentuk oleh perintis yang berjuang dari bawah.
Bahlil Lahadalia, dengan segala keterbatasan dan kontroversinya, telah memberi pelajaran penting bahwa dikepung elite bukan alasan untuk tunduk dan menyerah, melainkan menjadi energi untuk terus melangkah. Dalam setiap tegukan pahit, ada rasa yang membekas, dan mungkin di situlah esensi sejati dari politik yang manusiawi. (*)

































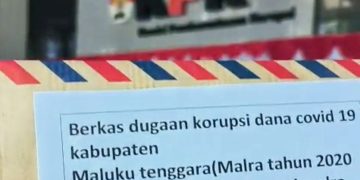




























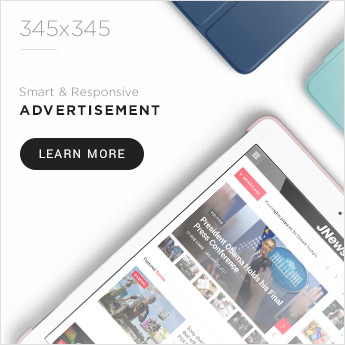















Discussion about this post